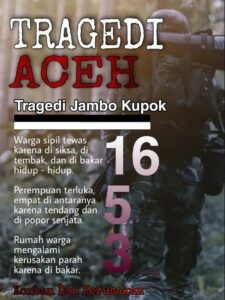Tenda Pengungsi Banjir Aceh Jadi Simbol Gagalnya Negara Pascabencana

Kondisi Tenda Pengungsian yang baru dipasok pihak Kecamatan Langkahan di Dusun Kareung, Gampong Buket Linteung, Sabtu (21/12/2025). (Foto:dok.Camat).
THE ATJEHNESE – Di balik klaim-klaim optimistis pemerintah pusat tentang penanganan bencana, ribuan warga Aceh justru masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang tidak layak, berbulan-bulan setelah banjir besar melanda. Realitas di lapangan menunjukkan jurang yang lebar antara pidato pejabat di Jakarta dan penderitaan nyata masyarakat di wilayah terdampak.
Banjir besar yang menerjang Aceh sejak akhir November 2025 tidak hanya menghancurkan rumah, lahan pertanian, dan infrastruktur publik, tetapi juga merobek martabat warga yang dipaksa bertahan hidup di tenda darurat dengan kondisi minim. Hingga kini, di sejumlah kabupaten, pengungsi masih tidur beralaskan terpal, berdesakan, dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan dasar.
Ironisnya, di saat rakyat Aceh masih bergulat dengan lumpur dan ketidakpastian, pemerintah pusat justru tampil dengan sikap seolah-olah bencana telah tertangani. Tidak ada penetapan status bencana nasional, tidak ada percepatan rehabilitasi yang terukur, dan tidak ada kebijakan luar biasa yang sebanding dengan skala kehancuran yang terjadi. Yang tersisa hanyalah bantuan darurat yang sporadis dan janji-janji normatif tanpa tenggat jelas.
Tenda pengungsian kini menjadi simbol paling telanjang dari kegagalan negara. Tenda-tenda itu bukan sekadar tempat berteduh sementara, melainkan bukti bahwa negara memilih menunda tanggung jawabnya. Anak-anak tumbuh dalam kondisi tidak layak, lansia bertahan tanpa kepastian layanan kesehatan berkelanjutan, dan perempuan harus menghadapi risiko kesehatan serta keamanan di ruang pengungsian yang tidak manusiawi.
Pemerintah pusat berulang kali menyatakan bahwa penanganan bencana telah “sesuai prosedur”. Namun prosedur siapa yang dimaksud, ketika ribuan warga masih menggigil di malam hari, sementara anggaran rehabilitasi belum juga turun? Prosedur itu terasa lebih sebagai tameng birokrasi ketimbang instrumen penyelamatan manusia.
Lebih menyakitkan lagi, sikap pemerintah pusat terkesan defensif dan arogan. Alih-alih mendengar jeritan daerah, pemerintah justru sibuk membangun narasi bahwa daerah mampu menangani sendiri. Sikap ini tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Aceh tidak kekurangan pengalaman menghadapi bencana, tetapi skala banjir kali ini jelas melampaui kapasitas normal daerah. Menolak mengakui itu adalah bentuk kesombongan politik yang dibayar mahal oleh rakyat.
Rehabilitasi pascabanjir berjalan lambat dan tanpa peta jalan yang transparan. Rumah-rumah rusak belum diperbaiki, lahan pertanian masih tertutup lumpur, dan infrastruktur vital dibiarkan rapuh menghadapi musim hujan berikutnya. Dalam kondisi ini, tenda pengungsi tidak lagi bisa disebut “sementara”, melainkan menjadi ruang tunggu panjang bagi janji negara yang tak kunjung datang.
Banjir Aceh seharusnya menjadi alarm nasional tentang krisis tata kelola lingkungan dan bencana. Namun alih-alih dijadikan momentum evaluasi menyeluruh, pemerintah pusat memilih jalan aman: meredam isu, menormalisasi penderitaan, dan menghindari keputusan politik besar. Sikap ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan pengingkaran terhadap kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warganya.
Selama pemerintah pusat terus memelihara jarak, memuja prosedur, dan menutup mata terhadap realitas di tenda-tenda pengungsian, maka rehabilitasi pascabanjir Aceh hanyalah ilusi. Negara boleh sombong dengan laporan di atas kertas, tetapi rakyat Aceh hidup dengan kenyataan pahit di bawah terpal.
Dan selama tenda-tenda itu masih berdiri, selama pengungsi masih menunggu, satu hal menjadi terang: yang gagal bukan hujan, melainkan negara.