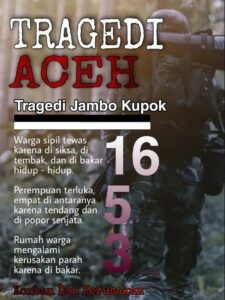Perampasan Rekaman Oleh TNI terhadap Jurnalis Kompas TV Dinilai Pelanggaran Berat UU Pers

FOTO ILUSTRASI.NET
THE ATJEHNESE – Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh mengecam keras dugaan perampasan alat kerja, intimidasi, hingga penghapusan paksa rekaman milik jurnalis Kompas TV Aceh, Davi Abdullah, yang diduga dilakukan oleh sejumlah anggota TNI di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM), Kamis (11/12/2025). Tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kekerasan terhadap jurnalis sekaligus penghalangan serius terhadap kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang.
Koordinator KKJ Aceh, Rino Abonita, dalam pernyataan resminya menyebut peristiwa ini sebagai preseden berbahaya bagi kebebasan pers, terlebih terjadi dalam situasi darurat bencana ketika publik justru membutuhkan informasi yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Insiden bermula ketika Davi Abdullah bersama timnya bersiap melakukan siaran langsung sekitar pukul 10.05 WIB di sekitar Lanud SIM. Saat merekam aktivitas di lokasi, Davi menangkap gambar kedatangan sejumlah orang yang membawa koper, beberapa di antaranya mengenakan atribut dengan emblem bendera Malaysia. Untuk memperoleh visual yang lebih jelas, Davi mendekat sebagaimana lazim dilakukan jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan.
Tak lama kemudian, sejumlah anggota TNI dan seorang yang mengaku sebagai intelijen menghampiri rombongan tersebut. Terjadi perdebatan terkait dokumen resmi rombongan, yang menurut keterangan tiga staf khusus gubernur, hendak menuju Aceh Tamiang untuk membantu penanganan banjir. Ketegangan meningkat ketika Aster Kasdam Iskandar Muda, Kolonel Inf Fransisco, meminta rombongan warga negara asing itu segera meninggalkan lokasi.
Seluruh rangkaian peristiwa tersebut direkam oleh Davi menggunakan telepon genggamnya. Namun, aktivitas jurnalistik itu justru berujung pada tindakan represif. Seorang anggota TNI AU mendatangi Davi dan memerintahkan agar rekaman dihapus. Davi menolak dan menegaskan dirinya bekerja sebagai jurnalis. Penolakan tersebut dibalas dengan tindakan intimidatif, mulai dari pemotretan identitas, tekanan verbal, hingga nada ancaman dari beberapa aparat.
Situasi kian memburuk ketika Kolonel Inf Fransisco kembali mendatangi Davi bersama sejumlah prajurit. Ia kembali memerintahkan penghapusan rekaman dan bahkan mengancam akan memecahkan telepon genggam milik jurnalis tersebut. Ponsel Davi kemudian dirampas dan diserahkan kepada provos TNI AU. Tanpa persetujuan pemiliknya, dua berkas rekaman berdurasi masing-masing sekitar empat menit dihapus. Setelah itu, ponsel dikembalikan dan aparat meninggalkan lokasi.
KKJ Aceh menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penyensoran langsung dan penghalangan kerja jurnalistik yang secara tegas dilarang oleh hukum. “Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tetapi pelanggaran hukum serius,” tegas Rino Abonita.
KKJ mengingatkan bahwa Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit melarang segala bentuk penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran. Bahkan, pelaku penghalangan kerja jurnalistik dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau dikenai denda maksimal Rp500 juta.
KKJ Aceh menegaskan bahwa aparat keamanan seharusnya tunduk pada undang-undang yang berlaku, bukan bertindak sewenang-wenang dengan dalih keamanan. Aparat wajib memahami bahwa pers bukan musuh negara, melainkan pilar demokrasi yang bertugas menyampaikan kebenaran kepada publik. Tidak ada alasan apa pun yang membenarkan intimidasi terhadap jurnalis yang sedang menjalankan tugasnya secara sah.
Dalam sikap resminya, KKJ Aceh menyampaikan delapan tuntutan, di antaranya: mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap jurnalis; mendesak aparat menghormati kerja pers, khususnya dalam situasi darurat bencana; meminta atasan Aster Kasdam IM menjatuhkan sanksi administratif sesuai UU Disiplin Militer; serta mendorong kepolisian memproses kasus ini sebagai delik umum. KKJ juga mengingatkan bahwa pihak yang keberatan atas pemberitaan seharusnya menempuh mekanisme hak jawab atau koreksi, bukan intimidasi.
KKJ Aceh merupakan bagian dari KKJ Indonesia yang dibentuk pada 14 September 2024 dan beranggotakan berbagai organisasi jurnalis serta elemen masyarakat sipil. Bergabungnya AJI Bireuen dan AJI Lhokseumawe pada Juli 2025 semakin memperkuat barisan advokasi keselamatan jurnalis di Aceh.
Kasus ini kembali menegaskan bahwa kebebasan pers di Indonesia masih rentan dilanggar, bahkan oleh aparat negara. Jika praktik intimidasi semacam ini dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum yang tegas, maka bukan hanya jurnalis yang terancam, tetapi juga hak publik untuk mengetahui kebenaran.
Perampasan alat kerja, penghapusan paksa rekaman, dan intimidasi terhadap jurnalis Kompas TV Aceh, Davi Abdullah, oleh aparat TNI di Lanud Sultan Iskandar Muda bukan sekadar insiden individual. Peristiwa ini adalah tamparan keras bagi kebebasan pers, sekaligus indikasi kegagalan aparat negara memahami batas kewenangan dalam negara hukum demokratis.
Dalam situasi darurat bencana—ketika publik sangat membutuhkan informasi yang transparan dan akuntabel—aparat justru memilih jalan pintas: membungkam pers dengan intimidasi. Ini bukan hanya keliru, tetapi berbahaya. Negara yang membiarkan aparatnya menyensor jurnalis dengan ancaman dan kekerasan adalah negara yang sedang melangkah mundur dari prinsip demokrasi.
Harus ditegaskan secara terang-benderang: tidak ada satu pun alasan hukum yang membenarkan aparat keamanan merampas, menghapus, atau mengintimidasi jurnalis yang sedang menjalankan tugas liputan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit melarang penyensoran dalam bentuk apa pun. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Ketika aparat melanggar ini, maka yang terjadi bukan lagi “kesalahpahaman lapangan”, melainkan pelanggaran hukum oleh aparatur negara.
Dalih keamanan, stabilitas, atau kerahasiaan tidak bisa digunakan secara serampangan untuk membungkam pers. Jika setiap kamera jurnalis dianggap ancaman, maka yang bermasalah bukan persnya, melainkan mentalitas kekuasaan yang anti-transparansi. Aparat keamanan seharusnya menjadi pelindung konstitusi, bukan aktor yang justru menginjak-injaknya.
Lebih mengkhawatirkan lagi, tindakan ini dilakukan secara terbuka, berlapis, dan berulang mulai dari permintaan penghapusan rekaman, ancaman perusakan alat kerja, hingga penghapusan paksa oleh provos. Ini menunjukkan bukan refleks sesaat, melainkan praktik yang lahir dari budaya impunitas: keyakinan bahwa aparat bisa bertindak tanpa konsekuensi hukum.
Jika tindakan semacam ini dibiarkan, pesan yang sampai ke publik sangat jelas dan berbahaya: meliput fakta bisa berujung intimidasi; menyampaikan kebenaran bisa berakhir pada ancaman. Ini bukan hanya ancaman bagi jurnalis, tetapi juga bagi hak publik untuk tahu.
Aparat keamanan wajib tunduk pada hukum sipil dan menghormati pers sebagai peliput kebenaran, bukan memperlakukannya sebagai musuh. Ketidaknyamanan terhadap liputan tidak boleh dibalas dengan represi. Mekanisme yang sah telah disediakan oleh hukum: hak jawab, hak koreksi, dan jalur hukum bukan intimidasi, bukan penyitaan, apalagi penghapusan paksa.
Kasus ini harus diproses secara terbuka dan tuntas. Sanksi administratif saja tidak cukup bila terbukti terjadi pelanggaran pidana. Negara tidak boleh absen ketika aparatnya melanggar hukum. Tanpa penegakan hukum yang tegas, kekerasan terhadap jurnalis akan terus berulang, dan demokrasi akan terus terkikis, sedikit demi sedikit.
Pers bukan ancaman. Pers adalah alarm publik. Dan negara yang mematikan alarmnya sendiri sedang mempertaruhkan masa depan demokrasi itu sendiri.