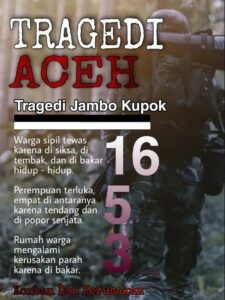Banjir Bandang Hantam Pertanian Aceh, Sawah Gagal Panen dan Negara Dinilai Gagal Lindungi Petani

Lahan pertanian rusak dan petani gagal panen akibat banjir (dok/antara).
THE ATJEHNESE – Bencana banjir bandang yang melanda berbagai kabupaten/kota di Aceh sejak akhir November lalu tidak hanya menyisakan lumpur dan genangan air, tetapi juga kehancuran besar di sektor pertanian. Ribuan petani kehilangan sumber penghidupan setelah sawah dan kebun mereka rusak parah, sementara respons negara dinilai belum sebanding dengan skala kerugian yang terjadi.
Data sementara menunjukkan kerusakan terparah menimpa komoditas padi sawah. Total lahan sawah yang terdampak banjir mencapai 89.582 hektare, angka yang mencerminkan krisis serius pada lumbung pangan daerah. Lumpur tebal yang terbawa banjir bandang menutup areal persawahan hingga ketinggian lebih dari satu meter, menyebabkan tanaman padi mengalami puso massal.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, mengungkapkan bahwa dari total luas baku sawah Aceh sebesar 202.811 hektare, hanya sebagian kecil lahan terdampak yang masih bisa diselamatkan.
“Dari 89.582 hektare yang terkena banjir, hanya sekitar 62.517 hektare yang masih bisa ditanami kembali. Sementara 27.065 hektare tidak bisa ditanami sama sekali karena tertutup lumpur tebal. Bahkan bantaran sawah tertimbun lumpur hingga 1 sampai 1,5 meter,” kata Cut Huzaimah, Senin (23/12/2025).
Ia menegaskan bahwa karakter banjir kali ini jauh lebih merusak dibanding banjir musiman biasa. Jika pada umumnya padi masih bisa bertahan meski terendam air selama beberapa hari, banjir bandang yang membawa lumpur menjadikan seluruh tanaman tak mungkin diselamatkan.
“Ini bukan banjir biasa. Semua yang ditanam itu puso total karena lumpur. Kalau hanya tergenang air, padi masih bisa bertahan tiga hari. Tapi yang ini sudah tidak mungkin diselamatkan,” ujarnya.
Dampak ekonomi dari kerusakan tersebut sangat besar. Estimasi kerugian sementara khusus untuk sektor sawah telah menembus Rp1,164 triliun. Angka ini belum termasuk kerugian tidak langsung, seperti hilangnya pendapatan petani, tertundanya musim tanam, serta ancaman terhadap ketahanan pangan daerah.
Ironisnya, banyak petani sebenarnya berada di fase menjelang panen. Curah hujan ekstrem dan buruknya sistem pengendalian banjir membuat hasil kerja berbulan-bulan hilang dalam hitungan jam. Hingga kini, belum ada kejelasan skema ganti rugi atau perlindungan menyeluruh dari pemerintah bagi petani yang kehilangan mata pencaharian.
Selain padi sawah, banjir juga menghantam komoditas pertanian lain. Lahan jagung terdampak seluas 767 hektare di empat kabupaten. Tanaman hortikultura seperti cabai, bawang, dan kentang rusak di 1.009 hektare yang tersebar di 11 kabupaten/kota. Sektor perkebunan pun tak luput, dengan kerusakan pada kakao, kelapa, dan kopi mencapai 13.023 hektare.
Total lahan pertanian dan perkebunan yang tercatat di Posko Tanggap Darurat mencapai 14.799 hektare, dan angka ini masih berpotensi bertambah seiring pendataan lanjutan.
Cut Huzaimah mengakui bahwa data kerugian tersebut belum final dan masih terus bergerak. Namun kondisi di lapangan sudah cukup untuk menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan risiko bencana dan perlindungan sektor pertanian.
Banjir bandang yang berulang dari tahun ke tahun memunculkan pertanyaan serius: di mana peran negara dalam menjaga tata kelola lingkungan, sistem drainase pertanian, serta mitigasi bencana? Petani kembali menjadi korban paling awal dan paling berat, sementara kebijakan pencegahan dan pemulihan berjalan lamban.
Tanpa intervensi serius berupa bantuan langsung, rehabilitasi lahan, serta evaluasi menyeluruh terhadap tata ruang dan pengendalian banjir, krisis ini berpotensi berlanjut ke krisis pangan dan kemiskinan struktural di pedesaan Aceh. Bagi petani, banjir kali ini bukan sekadar bencana alam—melainkan kegagalan negara dalam melindungi tulang punggung pangan daerah.