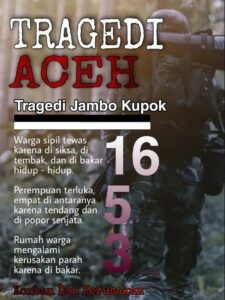Banjir Aceh dan Kejahatan Lingkungan yang Dibiarkan Negara

Foto udara menampilkan tumpukan kayu-kayu memenuhi area Pondok Pesantren Darul Mukhlishin pascabanjir bandang di Desa Tanjung Karang, Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Jumat (5/12/2025). Usai sepekan setelah bencana banjir bandang, akses menuju Desa Tanjung Karang masih terhambat akibat banyaknya tumpukan pohon dan lumpur tebal dari Sungai Tamiang sehingga bantuan sulit masuk ke wilayah tersebut. antara foto/Erlangga Bregas
THE ATJEHNESE – Tragedi banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh sejak akhir November 2025 telah berubah menjadi krisis kemanusiaan yang dalam dan berkepanjangan. Bukan hanya karena hujan deras semata, tetapi juga akibat keserakahan struktural yang berakar pada perusakan lingkungan dan kebijakan yang abai terhadap konservasi hutan di hulu. Akibatnya, rumah-rumah hancur, ribuan jiwa terlantar, dan ratusan keluarga kehilangan anggota keluarga mereka sementara pemerintah pusat tampak lebih sibuk menjaga citra ketimbang menyelamatkan rakyatnya sendiri.
Menurut data terbaru BNPB dan laporan institusi kemanusiaan, bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah menewaskan hampir 1.000 jiwa secara nasional, termasuk ratusan korban di Aceh. Hingga pertengahan Desember 2025, sekitar 990 orang dipastikan meninggal dunia, 225 masih hilang, dan lebih dari 5.100 orang luka-luka akibat banjir dan longsor, sementara 833,9 ribu warga masih mengungsi di berbagai posko pengungsian di Sumatra.
Di Aceh sendiri, korban jiwa terdampak mencapai ratusan orang dengan ribuan rumah rusak dan hancur total. Banyak komunitas harus meninggalkan kampung halaman mereka karena kedalaman air yang melampaui atap rumah, akses jalan yang putus, serta infrastruktur publik yang luluh lantak. Laporan lokal menyebutkan ribuan rumah di Kabupaten Aceh Utara saja mengalami kerusakan berat hingga ringan, puluhan ribu warga mengungsi, dan banyak desa terisolasi oleh lumpur dan reruntuhan material banjir.
Pengungsian Berkepanjangan di Tengah Krisis Kemanusiaan
Ratusan ribu warga Aceh yang kehilangan tempat tinggal kini hidup di tenda-tenda pengungsian yang jauh dari layak. Mereka tidak hanya berjuang melawan dinginnya malam dan minimnya fasilitas dasar, tetapi juga trauma psikologis atas kehilangan harta, sanak keluarga, dan masa depan yang tak lagi jelas. Banyak dari pengungsi ini belum menerima bantuan yang memadai, justru terjebak dalam birokrasi yang bertele-tele dan distribusi logistik yang lambat.
Situasi air bersih, sanitasi, makanan, dan layanan kesehatan tetap menjadi persoalan besar. Meski BNPB telah mengerahkan ratusan tenaga kesehatan relawan untuk penanganan darurat, dengan sekitar 794 tenaga kesehatan bertugas di lokasi terdampak di Aceh mayoritas berasal dari relawan karena dukungan struktural masih minim kebutuhan medis di pengungsian terus melampaui capaian respons yang ada.
Keserakahan dan Kelalaian Pemerintah Pusat
Warga dan pengamat menilai bencana ini memperlihatkan kegagalan pemerintah pusat dalam melakukan mitigasi, konservasi lingkungan, dan tata ruang yang berkelanjutan. Kerusakan hutan di hulu sungai yang menjadi penyebab utama meluapnya debit air dinilai bukan sekadar bencana alam, tetapi bencana yang diperparah oleh tindakan manusia sendiri. Perusakan hutan untuk industri, perkebunan, dan kegiatan ekstraktif lainnya telah menjadikan lanskap alam Aceh rentan terhadap banjir besar seperti ini.
Kritik publik semakin keras ketika pemerintah pusat enggan menetapkan status Darurat Bencana Nasional, alih-alih membatasi respons pada level administratif yang lebih rendah. Kebijakan ini mengakibatkan lambannya aliran dana darurat, minimnya koordinasi logistik di titik pengungsian, dan terhambatnya percepatan rehabilitasi infrastruktur kritis seperti jalan, jembatan, dan fasilitas layanan dasar.
“Aturannya bilang bantuan datang, tapi realitanya kami masih hidup di bawah terpal lusuh, menunggu air bersih dan makanan dasar setiap hari,” kata seorang relawan di salah satu posko pengungsian di Aceh Utara, menggambarkan betapa jauh jurang antara narasi resmi dan kondisi nyata di lapangan.
Para ahli perubahan iklim dan kebijakan lingkungan menyebut bencana Aceh sebagai cerminan dari keserakahan struktural, di mana pembangunan tidak pernah diimbangi oleh penghormatan terhadap fungsi ekologis hutan dan sungai. Ketika hutan ditebang demi keuntungan jangka pendek, sungai-sungai kehilangan kemampuan menahan aliran air, dan masyarakat dan desa-desa di dataran rendah menjadi korban utama.
Kerusakan Material dan Tantangan Rehabilitasi
Dampak material dari bencana ini juga sangat parah. Puluhan ribu rumah rusak atau hilang, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, serta infrastruktur publik lainnya mengalami kerusakan hebat. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai triliunan rupiah di sektor pertanian saja, menambah daftar panjang kerugian sosial yang tak terhitung.
Tuntutan Akan Akuntabilitas dan Aksi Nyata
Hari ini, suara-suara desakan kepada pemerintah pusat untuk bertanggung jawab semakin lantang. Warga menuntut:
- Penetapan status Darurat Bencana Nasional yang sesungguhnya
- Percepatan dana rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital
- Perbaikan sistem peringatan dini dan mitigasi bencana
- Reformasi kebijakan pengelolaan hutan dan tata ruang yang berkelanjutan
Tidak ada lagi ruang bagi narasi birokratis yang mengaburkan fakta: bencana Aceh bukan hanya soal hujan deras, tetapi soal kerusakan lingkungan yang dipupuk oleh keputusan politik yang salah.
Di tengah tenda-tenda pengungsian yang memanjang dari Aceh Utara hingga Pidie Jaya, suara rakyat terdampak tetap satu: mereka menuntut keadilan, keselamatan, dan negara yang benar-benar hadir bukan sekadar janji di atas kertas.