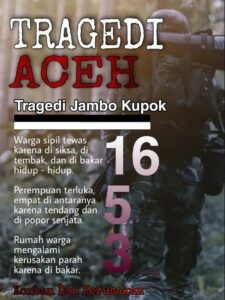Atjeh, Sejarah Panjang Kedaulatan yang Terpinggirkan oleh Narasi Negara

Tgk Hasan Tiro bersama sejumlah petinggi GAM di Swedia. Foto repro: Suparta dari dokumen pribadi
THE ATJEHNESE – Jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan pada 1945, Aceh telah berdiri sebagai entitas politik, keagamaan, dan ekonomi yang berdaulat. Aceh bukan wilayah kosong yang kemudian “dipersatukan”, melainkan sebuah peradaban tua dengan struktur negara, hukum, diplomasi, dan kekuatan militer yang diakui dunia internasional. Namun dalam historiografi resmi Indonesia, sejarah Aceh kerap diperkecil, disederhanakan, bahkan direduksi agar sesuai dengan narasi tunggal negara-bangsa yang dibangun dari Jakarta.
Pengaburan ini bukan sekadar kekeliruan akademik, melainkan kekerasan epistemic cara negara menata ingatan kolektif untuk menundukkan fakta sejarah yang tidak sejalan dengan ide integrasi sentralistik.
Akar Kedaulatan: Perlak sebagai Negara Islam Awal
Asal-muasal Aceh sebagai kekuatan politik dapat ditelusuri sejak berdirinya Kerajaan Perlak pada abad ke-9 Masehi. Perlak secara luas diakui dalam literatur sejarah sebagai kerajaan Islam tertua di Asia Tenggara, jauh mendahului negara-negara Islam lain di Nusantara.
Perlak bukan sekadar pusat keagamaan, melainkan negara pelabuhan internasional yang terhubung dengan jaringan perdagangan Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Dari Perlak berkembang sistem pemerintahan Islam, hukum berbasis syariat, dan jaringan ulama yang membentuk identitas politik Aceh. Fakta ini menegaskan bahwa Aceh lahir sebagai negara melalui proses sejarahnya sendiri, bukan sebagai produk kolonial atau konstruksi modern Indonesia.
Samudera Pasai: Negara Dagang yang Diakui Dunia
Perlak kemudian terhubung secara historis dan genealogis dengan Samudera Pasai, yang berdiri pada abad ke-13 dan berkembang menjadi pusat perdagangan dan keilmuan Islam di kawasan Samudra Hindia. Pasai memiliki mata uang emas (dirham) yang beredar luas indikator klasik kedaulatan ekonomi dalam hukum internasional pra-modern.
Para pedagang Eropa, Timur Tengah, dan Asia Selatan mencatat Pasai sebagai negara berdaulat, bukan koloni atau wilayah tak bertuan. Dengan demikian, Aceh telah menjadi bagian dari sistem global berabad-abad sebelum konsep Indonesia muncul pada abad ke-20.
Aceh Darussalam: Negara Kuat dengan Diplomasi Global
Puncak kekuatan politik Aceh terwujud dengan lahirnya Kesultanan Aceh Darussalam pada awal abad ke-16. Di bawah kepemimpinan para sultan besar terutama Sultan Iskandar Muda, Aceh menjelma menjadi kekuatan regional utama di Asia Tenggara.
Aceh memiliki:
- Angkatan laut yang kuat
- Sistem hukum dan administrasi negara
- Hubungan diplomatik resmi dengan Kesultanan Utsmani
- Perjanjian dan konflik terbuka dengan Portugis, Belanda, dan Inggris
Semua ini menunjukkan satu hal mendasar: Aceh bertindak sebagai subjek hukum internasional, bukan objek kekuasaan. Aceh berperang dan berunding atas namanya sendiri.
Perang Aceh: Ditaklukkan, Bukan Bergabung
Ketika Belanda melancarkan agresi militer pada 1873, Aceh melawan selama lebih dari tiga dekade dalam Perang Aceh (1873–1904) salah satu perang kolonial terpanjang dan paling brutal di Asia. Aceh tidak pernah menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan secara sah. Aceh ditaklukkan secara militer, bukan menyerahkan diri secara politik.
Fakta ini sangat penting, namun kerap diabaikan negara. Sebab jika diakui secara jujur, maka klaim integrasi Aceh ke dalam Indonesia sebagai kelanjutan alami sejarah menjadi problematik secara hukum dan moral.
Pascakemerdekaan: Sejarah Direduksi, Hak Dikebiri
Dalam konstruksi sejarah resmi Indonesia pascakemerdekaan, Aceh direpresentasikan sebatas “daerah” yang beruntung menjadi bagian republik. Kontribusi Aceh pada masa awal Republik, dukungan dana, logistik, bahkan pesawat untuk negara yang baru lahir diakui sebatas simbol, tetapi tidak diikuti pengakuan substantif terhadap kekhususan sejarah dan kedaulatannya.
Pemerintah Indonesia memilih narasi integrasi alih-alih kejujuran historis. Akibatnya, kebijakan negara terhadap Aceh kerap tidak sensitif terhadap:
- Tradisi kedaulatan lokal
- Sejarah perlawanan terhadap kekuasaan eksternal
- Hak pengelolaan sumber daya
- Trauma kolonial dan militerisme
Dampak Nyata: Konflik, Ketidakadilan, dan Ketidakpercayaan
Pengaburan sejarah Aceh bukan persoalan masa lalu semata. Ia berdampak langsung pada kebijakan hari ini dari konflik bersenjata, pelanggaran HAM, pengelolaan sumber daya alam, hingga penanganan bencana yang sering mengabaikan suara dan kepentingan Aceh.
Ketika negara gagal membaca Aceh sebagai subjek sejarah, Aceh diperlakukan sebagai objek kebijakan. Dari sinilah lahir ketegangan struktural yang terus berulang.
Penutup: Sejarah sebagai Tuntutan Keadilan
Aceh bukan wilayah tanpa identitas yang menunggu dibentuk oleh negara. Aceh adalah peradaban yang telah membentuk dirinya sendiri melalui kerajaan, hukum, perdagangan, dan perlawanan—jauh sebelum Republik Indonesia berdiri.
Mengabaikan fakta ini bukan hanya kesalahan akademik, tetapi ketidakadilan historis. Selama Pemerintah Indonesia terus membangun kebijakan tanpa berpijak pada sejarah Aceh yang sesungguhnya, maka konflik, resistensi, dan ketidakpercayaan akan terus muncul dalam berbagai bentuk.
Sejarah Aceh sebelum Indonesia merdeka bukan nostalgia romantik. Ia adalah kunci memahami tuntutan martabat, keadilan, dan pengakuan bahwa Aceh layak diperlakukan bukan sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai subjek sejarah.