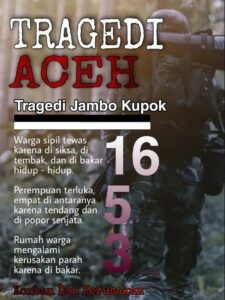Aceh Tenggelam, Banjir Hebat Ungkap Kejahatan Pembalakan Liar

Foto Warga
THE ATJEHNESE – Deru banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa pekan terakhir meninggalkan jejak yang lebih jujur daripada seribu laporan resmi: potongan-potongan kayu gelondongan yang terbawa arus, menumpuk di halaman warga, tersangkut di jembatan, dan menutup aliran sungai. Kayu-kayu itu bukan sekadar sisa bencana; ia adalah bukti hidup dari pembalakan liar yang telah berlangsung lama dan dibiarkan merusak paru-paru terakhir Tanah Rencong.
Warga di Pidie, Aceh Besar, dan Aceh Tenggara mengaku, setiap kali banjir datang, mereka seolah menyaksikan potret kehancuran hutan yang dibawa langsung oleh air. Gelondongan besar dengan diameter puluhan sentimeter mengalir deras seperti benda tak bernyawa, namun menyimpan kisah panjang: tentang perambahan, tentang lemahnya pengawasan, dan tentang betapa hutan Aceh kini kian tak mampu lagi melindungi dirinya.
“Ini kayu ilegal, bukan kayu hanyut biasa,” ujar seorang warga yang rumahnya terendam hingga pinggang. “Kalau hutannya masih sehat, air tidak akan seganas ini.”
Bencana yang terjadi bukan hanya soal curah hujan ekstrem, tetapi akibat dari hilangnya lapisan penyangga alam. Di kawasan yang dulunya dihuni rimbunnya pepohonan dan pepohonan tua, kini yang tersisa hanyalah lereng terjal yang mudah longsor dan sungai yang tak lagi mampu menahan luapan air.
Para pemerhati lingkungan sejak lama memperingatkan bahwa Aceh sedang berada dalam fase krisis ekologis, terutama setelah temuan banyaknya jalur loging ilegal, pembukaan lahan tanpa izin, serta aktivitas pembalakan yang berada tak jauh dari kawasan konservasi bahkan Taman Nasional Gunung Leuser. Namun, peringatan demi peringatan itu kerap tenggelam dalam hiruk pikuk kepentingan kelompok tertentu.
Yang membuat kondisi semakin memprihatinkan adalah kenyataan bahwa sebagian kayu hasil kejahatan lingkungan ini seolah mendapatkan “jalur aman” menuju pemukiman — bukan lagi dalam bentuk gelondongan liar yang terbawa banjir, tetapi sebagai bahan bangunan murah yang beredar di pasar gelap. Kayu yang dulu berdiri kokoh di belantara kini berubah menjadi sekat rumah, tiang bangunan, hingga perabot yang menyimpan kisah pilu tentang hutan yang ditebang hingga tinggal nama.
Pakar kehutanan menegaskan bahwa pola kerusakan ini tidak mungkin terjadi jika hanya dilakukan oleh penebang kecil atau warga desa. Skala pembalakan, alur distribusi, dan keberanian melibas kawasan hutan strategis menunjukkan adanya operasi terorganisir, bahkan melibatkan jaringan yang mengetahui titik lemah pengawasan negara.
Di sisi lain, bencana yang terus berulang semakin menekan masyarakat kecil. Pertanian rusak, anak-anak terpaksa mengungsi, akses jalan terputus, dan kegiatan ekonomi lumpuh. Yang paling ironis, justru masyarakat lapis bawah yang menanggung beban dari kejahatan ekologis yang dilakukan segelintir pelaku yang tak pernah tersentuh hukum.
Kini, masyarakat Aceh menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak lagi berhenti pada janji penindakan, tetapi benar-benar menghadirkan sistem pengawasan ketat, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan pemulihan kawasan hutan secara menyeluruh. Sebab tanpa langkah-langkah tegas, banjir besar yang terjadi tahun ini hanya akan menjadi pembuka dari rangkaian bencana yang lebih parah di masa mendatang.
Hutan Aceh tidak hanya warisan alam, tetapi juga benteng terakhir yang menjaga kehidupan masyarakat. Jika hutan terus dirampas, maka banjir dan longsor bukan lagi bencana alam, melainkan bencana akibat kelalaian manusia.