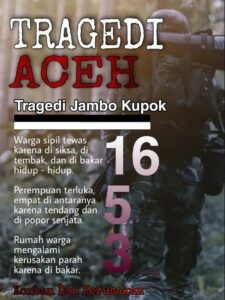Kasus Rumoh Geudong Dalam Perspektif 3 Tokoh Hukum Internasional Dunia

Personel Brimob menyusuri sekitar area Rumoh Geudong, Pidie, Aceh, jelang kedatangan Presiden Jokowi. (Arsip Istimewa/Polda Aceh via detikcom)
THE ATJEHNESE – Sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan mekanisme integral dalam menegakkan hukum serta keadilan yang mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum (rule of law). Akan tetapi, dalam praktiknya, sistem ini seringkali menghadapi persoalan mendasar dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama pada konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat.
Salah satu kasus yang menonjol serta menjadi luka sejarah bangsa adalah kasus pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong (Aceh), Aceh pada masa konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia serta Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1989–1998.
Rumoh Geudong (Aceh), yang terletak di Pidie, Aceh, dikenal sebagai salah satu tempat terjadinya penyiksaan serta pelanggaran HAM berat oleh aparat keamanan terhadap warga sipil. Berdasarkan laporan Komnas HAM serta berbagai lembaga hak asasi manusia, tempat ini dijadikan pusat interogasi serta penahanan di luar hukum (extrajudicial detention) terhadap masyarakat sipil yang diduga simpatisan GAM.
Tindakan penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, serta kekerasan seksual yang terjadi di Rumoh Geudong (Aceh) menjadi bukti konkret gagalnya sistem peradilan pidana dalam menjamin prinsip due process of law serta non-derogable rights( hak yg tidak dapat dikurangi) sebagaimana dijamin oleh Konstitusi serta instrumen internasional HAM.
KKR Aceh menyerahkan sekitar 5.193 data korban pelanggaran HAM di Aceh (termasuk Rumoh Geudong) kepada tim penyelesaian. Dengan rincian sebagai berikut Korban Minimal 133 orang dari 55 Kartu Keluarga, di Kabupaten Pidie.
Dan sebanyak 55 Orang sudah menjalani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk kasus pelanggaran HAM berat rumoh geudong tersebut. Adapun pelanggaran yang dilakukan yaitu seperti : Penyiksaan keji, penembakan, Pemerkosaan, kekerasan seksual, digantung terbalik, tubuh di setrum, serta pembunuhan. Data diatas hanya yang ditemukan, pada dasarnya korban jauh lebih banyak yang tidak ditemukan
Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum formal, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan keadilan substantif bagi korban serta masyarakat. Akan tetapi, hingga kini penyelesaian kasus Rumoh Geudong (Aceh) masih mengalami stagnasi di tingkat penegakan hukum, baik oleh Kejaksaan Agung maupun Pengadilan HAM ad hoc. Kondisi ini menunjukkan adanya problem struktural, politik, serta yuridis dalam mekanisme pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.
Oleh karena itu, kajian terhadap sistem peradilan pidana dalam perspektif HAM menjadi sangat relevan untuk mengkaji sejauh mana sistem tersebut mampu menjamin perlindungan hak korban, menegakkan akuntabilitas pelaku, serta memenuhi prinsip keadilan transisional (transitional justice) di Indonesia.
Tragedi Rumoh Geudong (Aceh) menjadi simbol kekejaman serta impunitas dalam penegakan hukum di Indonesia. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru serta penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada tahun 2005, muncul harapan besar bahwa keadilan bagi korban akan ditegakkan melalui mekanisme Pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Namun hingga kini, tidak ada satu pun pelaku yang dibawa ke pengadilan. Proses penyelidikan Komnas HAM yang telah dilakukan sejak tahun 2002 bahkan belum berujung pada penyidikan, menunjukkan adanya kebuntuan dalam sistem hukum nasional. Kegagalan tersebut bukan hanya masalah prosedural, tetapi mengindikasikan adanya persoalan struktural serta kultural yang lebih dalam.
Dalam konteks inilah, teori sistem hukum Teori Keadilan John Rawls serta Teori Negara Hukum (Rechtsstaat) serta Teori Lawrence M. Friedman menjadi relevan untuk digunakan. Teori – teori tersebut menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan formal (substansi hukum), tetapi juga oleh kekuatan lembaga penegak hukum (struktur) serta kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum). Dan menjelaskan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di Rumoh Geudong (Aceh) mewakili ketidakadilan struktural, di mana warga sipil paling lemah menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan.
Serta Rumoh Geudong (Aceh) menunjukkan negara tidak berfungsi sebagai Rechtsstaat, karena hukum tidak melindungi warga negaranya serta aparat bertindak sewenangwenang.
Dengan menganalisis kasus Rumoh Geudong (Aceh) melalui lensa teori John RawIs, Rechtsstaat, Friedman, penelitian ini berusaha memahami akar kegagalan sistem hukum Indonesia dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat di Aceh.
- Eksponen serta Pokok Pikiran Utama Teori
1. Teori keadilan yang dikembangkan oleh John Rawls dalam karya A Theory of Justice (1971) merupakan salah satu fondasi terpenting dalam filsafat hukum modern. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa keadilan bukan sekadar persoalan distribusi hak serta kewajiban, tetapi juga persoalan bagaimana struktur dasar masyarakat (basic structure of society) diatur agar dapat menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu. Dalam konteks ini, Rawls mengajukan prinsip keadilan yang disebut justice as fairness, yaitu keadilan yang didasarkan pada kewajaran, kesetaraan, serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Rawls menegaskan dua prinsip keadilan yang saling melengkapi:
Prinsip Kebebasan yang Sama (Equal Basic Liberties Principle), yaitu setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seperti hak hidup, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, serta hak untuk tidak disiksa serta diperlakukan secara kejam.
Prinsip Perbedaan (Difference Principle), yaitu ketimpangan sosial hanya dapat dibenarkan jika membawa manfaat bagi mereka yang paling lemah dalam masyarakat.
Dalam konteks pelanggaran HAM berat di Rumoh Geudong (Aceh), Aceh, kedua prinsip tersebut memberikan landasan moral serta hukum yang kuat untuk menilai kegagalan negara dalam menjamin hak asasi warga sipil. Selama operasi militer di Aceh pada periode 1989–1998, aparat keamanan melakukan tindakan penangkapan, penahanan, penyiksaan, serta pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan dasar Rawls karena melanggar hak-hak non-derogable yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.
Lebih jauh, prinsip perbedaan Rawls mengharuskan negara berpihak kepada kelompok paling rentan — dalam hal ini korban pelanggaran HAM berat serta keluarganya. Negara seharusnya menggunakan kewenangannya untuk melindungi mereka yang paling lemah, bukan malah memperkuat ketimpangan dengan tindakan represif. Dalam kenyataannya, sistem peradilan pidana Indonesia justru menunjukkan bias kekuasaan, di mana pelaku yang memiliki jabatan struktural tidak tersentuh hukum, sedangkan korban kehilangan akses terhadap keadilan, rehabilitasi, serta kebenaran.
Konsep veil of ignorance (tirai ketidaktahuan) yang diperkenalkan Rawls juga penting untuk diterapkan dalam memahami keadilan di Aceh. Konsep ini menuntut para pembuat kebijakan serta penegak hukum untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mengetahui posisi sosial, etnis, atau politik mereka sendiri. Oleh karena itu, hukum yang dibuat akan bersifat netral serta adil bagi semua pihak. Jika konsep ini diterapkan dalam penyusunan kebijakan pasca-konflik Aceh, maka negara akan lebih menekankan pemulihan korban ketimbang kepentingan politik atau stabilitas semu.
Dalam kerangka sistem peradilan pidana, teori Rawls mengandung pesan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui penghukuman formal terhadap pelaku, melainkan juga harus menjamin keadilan substantif yaitu pemulihan martabat manusia serta pengakuan terhadap penderitaan korban. Oleh karena itu, penyelesaian kasus Rumoh Geudong (Aceh) seharusnya tidak berhenti pada aspek hukum positif, tetapi juga melibatkan proses keadilan transisional yang meliputi kebenaran, reparasi, serta jaminan ketidakberulangan.
Oleh karena itu, eksponen teori keadilan Rawls pada konteks HAM di Aceh dapat disarikan sebagai berikut:
Negara memiliki kewajiban moral untuk menjamin hak-hak dasar warga sipil, bahkan dalam kondisi konflik bersenjata.
Sistem peradilan pidana harus memprioritaskan perlindungan terhadap korban serta kelompok rentan, bukan kepentingan politik atau stabilitas negara.
Proses hukum harus bebas dari bias kekuasaan serta dijalankan berdasarkan asas kesetaraan di depan hukum.
Keadilan yang sejati hanya dapat tercapai apabila negara mengakui kesalahan masa lalu serta memberikan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.
Dengan menggunakan perspektif Rawls, tragedi Rumoh Geudong (Aceh) tidak hanya dilihat sebagai kegagalan penegakan hukum, tetapi juga sebagai krisis moral serta sosial akibat penyimpangan prinsip keadilan yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap kebijakan negara. Teori Rawls memberikan kerangka etis bahwa tanpa keadilan bagi korban, tidak akan ada perdamaian yang sejati serta berkelanjutan di Aceh maupun di Indonesia secara keseluruhan.
2 . Teori Negara Hukum atau Rechtsstaat adalah fondasi utama dalam filsafat hukum modern Eropa Kontinental, khususnya dikembangkan melalui pemikiran Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl, serta para tokoh hukum Jerman abad ke-19. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada negara. Dengan kata lain, supremasi hukum (rule of law) menjadi prinsip pokok, serta setiap tindakan negara harus berada dalam kerangka hukum yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, serta melindungi hak-hak asasi warga negara.
Prinsip-prinsip kunci teori Rechtsstaat meliputi:
Supremasi Hukum, yaitu semua tindakan pemerintah serta aparat keamanan harus berada di bawah kendali hukum, sehingga tidak ada individu atau institusi yang berada di atas hukum.
Persamaan di Hadapan Hukum, yaitu setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam menghadapi sistem hukum, tanpa diskriminasi politik, sosial, atau ekonomi.
Peradilan Independen, yaitu proses pengadilan harus bebas dari intervensi eksekutif, politik, atau pihak lain, agar keputusan hukum dapat menegakkan keadilan objektif.
Proteksi Hak Asasi, yaitu Hukum harus berfungsi sebagai sarana utama untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak hidup, kebebasan, serta perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang.
Dalam konteks Rumoh Geudong (Aceh), Aceh, penerapan prinsip-prinsip Rechtsstaat menjadi sangat relevan untuk menilai kegagalan sistem peradilan pidana Indonesia saat menghadapi pelanggaran HAM berat. Operasi militer yang dilakukan pada periode konflik Aceh (1989–1998) menunjukkan beberapa penyimpangan mendasar dari prinsip negara hukum:
Supremasi hukum tidak ditegakkan, yaitu aparat keamanan bertindak sewenang-wenang, melakukan penangkapan serta penyiksaan tanpa proses hukum yang sah. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum serta memperkuat budaya impunitas.
Persamaan di hadapan hukum dilanggar, yaitu pelaku yang memiliki kedudukan struktural atau politik tertentu bebas dari proses hukum, sementara korban, yang merupakan warga sipil biasa, tidak memiliki akses keadilan.
Peradilan independen terganggu, yaitu Intervensi politik serta tekanan militer mempengaruhi proses peradilan, sehingga hukum menjadi alat kekuasaan, bukan instrumen keadilan.
Hak asasi warga negara diabaikan, yaitu tindakan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta pembunuhan jelas melanggar hak hidup, kebebasan, serta perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara.
Penerapan teori Rechtsstaat pada kasus Rumoh Geudong (Aceh) menunjukkan perbedaan antara hukum formal serta keadilan substantif. Secara formal, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, termasuk Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil serta Politik (ICCPR). Akan tetapi, dalam praktiknya, supremasi hukum serta perlindungan hak asasi sering terabaikan ketika kepentingan segelintir penguasa serta impunitas lembaga dijadikan alasan utama.
Selain itu, teori Rechtsstaat menyediakan kerangka evaluasi yang kritis terhadap reformasi hukum pascakonflik Aceh. Menurut teori ini, upaya transitional justice (keadilan transisional) seperti pengungkapan kebenaran, rehabilitasi korban, serta pengakuan negara terhadap kesalahan masa lalu menjadi sangat penting. Tanpa penerapan prinsip negara hukum yang konsisten, reformasi hukum hanya akan bersifat simbolik serta tidak menyelesaikan akar permasalahan pelanggaran HAM.
Oleh karena itu, eksponen teori Rechtsstaat pada konteks Rumoh Geudong (Aceh) dapat disimpulkan sebagai berikut:
Negara wajib menegakkan supremasi hukum serta memastikan semua tindakan aparat berada dalam batas hukum.
Setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus bagi elite atau aparat.
Peradilan harus independen, bebas dari tekanan politik atau kekuasaan, untuk menjamin keputusan hukum yang adil.
Perlindungan hak asasi adalah tujuan utama hukum, serta kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban merupakan indikasi penyimpangan dari prinsip negara hukum.
Dengan mengaitkan teori Rechtsstaat ke kasus Rumoh Geudong (Aceh), terlihat jelas bahwa pelanggaran HAM berat tidak hanya merupakan kegagalan aparat, tetapi juga kegagalan institusional sistem hukum nasional. Teori ini memberi kerangka analisis yang kuat untuk menilai reformasi hukum, membangun sistem peradilan yang adil, serta memastikan hak asasi warga negara menjadi pusat perhatian negara.
3. Lawrence M. Friedman adalah salah satu tokoh penting dalam sosiologi hukum modern, yang menekankan bahwa hukum tidak bisa dipahami hanya sebagai norma tertulis (law in books), tetapi juga harus dianalisis melalui praktek nyata (law in action) dalam masyarakat. Pendekatan Friedman dikenal sebagai pendekatan sistem hukum (legal system approach), yang memansertag hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen utama: struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substantive law), serta budaya hukum (legal culture).
Komponen Teori Friedman serta Relevansinya
Struktur Hukum (Structure of Law)
Struktur hukum meliputi lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, serta aparat pemerintah. Dalam kasus Rumoh Geudong (Aceh), struktur hukum Indonesia menunjukkan kelemahan serius: aparat keamanan yang seharusnya menjadi bagian dari sistem hukum justru bertindak di luar koridor hukum, mengabaikan prosedur peradilan pidana, serta memicu pelanggaran HAM berat. Analisis Friedman menekankan bahwa kegagalan struktur hukum inilah yang membuat penegakan hukum formal tidak efektif.
Substansi Hukum (Substantive Law)
Substansi hukum mencakup aturan hukum tertulis, undang-undang, serta peraturan yang berlaku. Indonesia, secara formal, memiliki UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta berbagai instrumen HAM internasional. Akan tetapi, kasus Rumoh Geudong (Aceh) menunjukkan bahwa hukum formal tidak selalu diterapkan. Substansi hukum tidak cukup jika tidak didukung oleh mekanisme pelaksanaan serta penegakan yang efektif. Friedman menekankan bahwa perbedaan antara law in books serta law in action menjadi titik penting untuk memahami fenomena pelanggaran HAM.
Budaya Hukum (Legal Culture)
Budaya hukum adalah sikap, perilaku, serta nilai-nilai masyarakat serta aparat hukum terhadap hukum itu sendiri. Di Aceh selama konflik, budaya hukum aparat cenderung menekankan kepentingan keamanan serta loyalitas hierarkis daripada perlindungan hak asasi warga. Friedman menekankan bahwa budaya hukum yang permisif terhadap pelanggaran atau kekerasan akan melemahkan efektivitas hukum formal, sehingga pelanggaran HAM dapat berlangsung tanpa konsekuensi.
Aplikasi Teori Friedman pada Rumoh Geudong (Aceh)
Dengan mengaplikasikan teori Friedman, kasus Rumoh Geudong (Aceh) dapat dianalisis secara sistematis:
Dari sisi struktur hukum, aparat keamanan yang seharusnya melindungi warga sipil justru menjadi pelaku pelanggaran HAM. Pengadilan serta lembaga penegak hukum lainnya tidak mampu menjalankan fungsi kontrol secara efektif.
Dari sisi substansi hukum, undang-undang HAM serta mekanisme hukum yang tersedia tidak diterapkan secara konsisten, sehingga hukum formal tidak mencerminkan keadilan substantif.
Dari sisi budaya hukum, nilai-nilai yang mendukung impunitas, loyalitas kepada komando militer, serta pengabaian hak warga sipil mendominasi praktik penegakan hukum di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan HAM.
Sedikit tambahan bahwa jika perbuatan salah itu, mau dilihat dari hukum dan teori mana saja pun tetaplah akan salah, karena semua hukum berasal dari satu fikiran yg terang dan manusiawi. harapan kita bersama adalah segala pelanngaran HAM berat di mana saja bisa menemukan titik terang penanganannya.